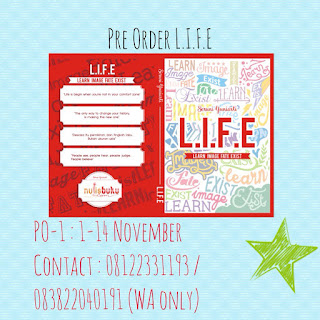Jakarta, Juni 2016
Hujan rintik-rintik,
embun yang menempel di kaca, dan musik jazz instrumen menemaniku menunggu
seseorang di sebuah kafe yang sangat memiliki banyak cerita buatku. Kafe tempat
dimana aku pertama kali bertemu dengan seorang laki-laki yang saat ini menjadi suamiku.
“hot caramel latte?” lamunanku seketika buyar ketika waitress membawakan pesananku.
“oh iya mas, terima kasih.”
Jawabku sembari menerima cangkir berwarna putih itu.
Sepeninggalan
waitress tersebut, pikiranku langsung
berjalan-jalan melewati lorong waktu. Aku selalu teringat bagaimana saat
pertama kali bertemu dengan Bagas, enam tahun lalu. Aku yang pada saat itu
sedang mencari data untuk materi skripsi hingga ke Universitas Negeri di Depok
dan akhirnya menyempatkan datang ke salah satu cafe di daerah Kemang sebelum akhirnya pulang ke Bandung. Ternyata
pada hari-hari tertentu di cafe itu
diadakan open mic (read : melawak
hanya dengan bercerita seorang diri di depan banyak orang) bagi orang-orang yang merasa dirinya lucu. Saat itu aku datang
dengan seorang teman yang ternyata adalah teman SMA Bagas, dan Bagas melakukan open mic yang tidak begitu aku
perhatikan saat itu.
*****
Jakarta, Februari 2010.
“itu Bagas ngapain?” kata Alisa
temanku tiba-tiba.
“hah? Siapa Bagas?” jawabku
dengan tatapan masih fokus pada laptop di depanku ini.
“temen SMA gue.” Balas Alisa,
matanya terus memandang panggung ala kadarnya yang ada di bagian depan cafe tersebut.
Aku
mendengar samar-samar sesuatu yang lucu, Alisa pun tidak sanggup menahan
ketawanya di sebelahku. Aku sendiri masih sibuk dengan skripsi dan laptopku
ini. Setelah Bagas selesai dengan lawakannya, Alisa dengan sigap memanggilnya
sambil melambai-lambaikan tangan.
“Gaass,” Alisa memanggilnya
dengan sedikit berteriak. Aku dapat melihat Bagas tersenyum sebentar dan
langsung menghampiri kami.
“Alisa? Apa kabar? Lagi apa?” tanyanya
sambil melihat kearahku dengan sekejap.
“abis dari UI, Gas. Nemenin temen
nyari data buat skripsinya. Nih kenalin,” Alisa memintaku untuk berdiri,
“Dinar,” jawabku sembari
mengulurkan tangan dan tersenyum.
“Bagas.” Jawabnya tak kalah
ramah.
“lo udah balik tinggal di
Jakarta, Gas?” Alisa kembali bertanya pada Bagas ketika kami bertiga sudah
duduk di meja yang sama.
“belum, Cha. Boro-boro skripsi aja gue belum ambil. Ini kebetulan gue lagi di
Jakarta aja. Gimana gue oke nggak tadi?” tanya Bagas sambil tertawa.
“hahahahaa lumayan lah Gas. By the way lo tadi ngapain sih? Ngelawak
kayak Sule gitu?”
Mendengar pertanyaan Alisa aku
kontan menahan tawa.
“hahahahhaha nggak kayak Sule
banget sih, Cha. Yang tadi gue lakuin itu namanya stand up comedy, kalau bingung itu apa bisa liat di Youtube atau Googling
aja. Jadi intinya stand up comedy tuh
salah satu tipe komedi yang pelawaknya ngebawain lawakan di panggung sendirian
biasanya dengan cara bermonolog atau story
telling sama penonton, gitu.” Bagas mencoba menjelaskan pada kami berdua.
“di Indonesia sendiri memang
belum setenar di luar sana sih, kalau di Amerika stand up comedy udah terkenal dari beberapa tahun lalu. Sedangkan
di kita masih baru banget, masih sedikit orang yang berani ngelakuin stand up comedy secara terang-terangan,
paling yang terkenal ya Pandji sama Raditya Dika doang.” Katanya melanjutkan. Aku dan Alisa fokus mendengarkan
sambil mengangguk-anggukan kepala, tanda mengerti.
Perawakan
Bagas itu kurus dan tinggi banget, rambutnya sedikit ikal dan pakai kacamata.
Bukan tipeku sih memang pada saat itu.
“kalian kapan balik Bandung?”
tanya Bagas setelah basa-basi kesana-kemari.
“malem ini sih rencananya,”
jawabku singkat.
“bawa kendaraan? Berdua doang?”
“iya Gas, Dinar bawa mobil.
Lagian dia udah biasa kok nyetir malem gini.” Kali ini giliran Alisa yang
menanggapi.
“serius? Kenapa nggak nginep dulu
di rumah lo, Cha?”
“gue ada kuliah besok, nggak bisa
ditinggal, Gas.”
“ohh..” katanya dengan tatapan
khawatir.
“udah gue anter aja deh sampai
Bandung, gue ngga akan bawa mobil dulu. Ya?” kata Bagas tiba-tiba hampir
membuat jantungku berhenti.
“eh nggak usah, kasian
ngerepotin.” Ucapku tanpa pikir panjang.
“nggak apa-apa, nggak akan gue
culik. Alisa kan kenal deket sama orang tua gue, santai aja.”
“iya, Nar. Udah nggak apa-apa
daripada lo nggak ada yang gantiin nyetir. Gue kan kalau malem rabun ayam.”
Jawab Alisa.
Sial nih anak. Aku tidak merespon pernyataan dari Alisa.
“iya, udah nggak apa-apa. Tapi
nanti anter gue ke rumah dulu ya, naro mobil.” Bagas kembali bersuara.
Dengan sigap Alisa menjawab,
“siap pak bos.” Sambil mengangkat tangannya, tanda menghormat.
Jadilah
saat itu kami pulang bertiga ke Bandung. Mulai saat itu juga hubunganku dengan
Bagas mulai dekat dan akhirnya memutuskan untuk pacaran.
*****
Bandung, Maret 2012
Malam itu suasana
makan malam tidak sehangat biasanya, tidak sesantai biasanya, tidak ada obrolan
kesana-kemari, tidak saling menanyakan kabar dan kegiatan hari itu. Sampai Ayah
menanyakan sesuatu yang sangat tidak ingin aku jawab,
“Bagas sebenarnya serius sama
kamu, Dinar?” pembahasaan yang kaku adalah ciri khas dari Ayah, dan semakin
membuatku ciut untuk menjawabnya. Tuhan, tolong aku.
“ya seperti itu lah Yah.” Jawabku
seadanya tanpa melihat mukanya sama sekali.
Ayah kembali bertanya, “seperti
itu bagaimana?” kali ini di tambah dengan tatapan Ibu yang menyuruhku untuk
menjawab dengan serius.
Aku menghela nafas sebelum
akhirnya menjawab, “ya, kami kan sudah usia segini yah. Pasti serius sih dalam
menjalani hubungan. Dinar sama Bagas memang ada rencana untuk lebih serius,
namun belum tau kapan.”
Tanpa pikir panjang, Ayah
langsung menjawab. “kamu mau menikah dengan seseorang yang kuliah strata satu
saja tidak selesai? Mau makan apa kamu nanti?”
Mendengar jawaban Ayah saat itu,
rasanya nasi yang sudah sampai kerongkongan ingin keluar lagi. Melihat ekspresi
mukaku Ibu langsung menganggapi,
“kami cuma ingin kamu mendapatkan
yang terbaik, Dinar. Jangan sampai dibutakan oleh cinta. Tuh lihat mas Adi
sudah jadi dokter, masa depannya akan lebih jelas daripada kamu menikah sama
komedian tidak jelas seperti itu.”
Glek. Ucapan Ibu saat itu rasanya
langsung menusuk hati. Aku tidak percaya bahwa ibu akan berkata seperti itu. Saat
itu adalah kali pertama aku sakit hati oleh perkataan Ibu. Sakit.
Tanpa pikir panjang aku langsung
membanting sendok di atas piring dan meninggalkan meja makan. Ayah mencoba
untuk memanggilku dengan sedikit berteriak, namun nampaknya Ibu mampu
menenangkan beliau.
Aku menangis
semalaman, Bagas tidak boleh tahu pembicaraanku di meja makan tadi, sangat
tidak boleh. Aku kecewa kepada orang tuaku, mereka hanya bisa melihat seseorang
dari materi yang mereka miliki, bukan apa yang sesungguhnya ada di dalam
dirinya.
Bagas memang akhirnya
di keluarkan karena tidak kunjung selesai menyelesaikan kuliahnya di
Universitas Negeri nomor 1 di Bandung. Pemikirannya yang terlalu kritis
menghambatnya untuk menyelesaikan perkuliahan di jurusannya, yaitu Bisnis dan
Management. Aku sendiri sangat menyayangkan ketika mengetahui dirinya harus
mengeluarkan diri kalau tidak mau dikatakan ‘dikeluarkan.’ Bagas sendiri pun
sangat terpukul dan menyesal, apalagi ketika ia harus berkata jujur kepada
orang tuanya mengenai kegiatan akademiknya yang tidak mulus. Akhirnya Papa
Bagas pun tidak memberikan kesempatan padanya untuk kembali berkuliah namun
memintanya agar fokus menjadi komika. Andaikan Ayah dan Ibu memiliki hati
selapang dan pemikiran seluas itu, bahwa hidup ini bukan hanyalah masalah uang
dan uang.
Sebenarnya
saat itu aku memahami apa yang dipikirkan oleh kedua orang tuaku. Saat itu
pekerjaan sebagai komika tidak semudah dan semulus sekarang. Tapi bukannya uang
tidak akan menjamin kebahagiaan?
*****
Bandung, April 2012
“jadi aku kapan nih bisa ngelamar
langsung ke orang tua kamu, Nar?” tanya Bagas suatu ketika saat kita sedang
makan di daerah Dago.
Saat itu memang Bagas sudah
menyatakan maksudnya untuk menikahiku secara unofficial. Bahkan Bagas sudah membelikan ku cincin sederhana yang
masih harus aku lepas ketika memasuki rumah, maafkan aku Bagas.
“hmm..” kataku tidak menjawab
pertanyaannya. Sebenarnya Bagas sudah menanyakan hal yang sama lebih dari
sepuluh kali, dan aku selalu tidak bisa menjawabnya.
“kok nggak di jawab, Nar?” tanyanya
lagi, kali ini sembari memandangku dengan lebih serius.
Aku masih tidak bisa menjawab,
dan malah memalingkan muka dari tatapannya.
“Dinar Putri Amanda. Aku nanya
serius ya sama kamu, kamu sayang kan sama aku? Beneran mau nikah kan sama aku?
Kalau nggak, yaudah aku mundur dari sekarang.” Tangan Bagas memegang kepalaku,
supaya aku melihat kearahnya. Sepertinya dia sudah mulai kesal dengan
tanggapanku selama ini.
Aku hanya bisa menangis dan
menjawab seadanya, “aku nggak bisa ngelawan Ayah, Gas.”
Bagas melepaskan tangannya dari
mukaku, dan membantingkan tubuhnya kesandaran kursi.
“yaudah kalau gitu, aku bisa
bilang apa, Nar.” Volume suara Bagas berubah seketika saat merespon
pernyataanku.
Aku kembali terdiam.
Pernyataan Bagas selanjutnya
semakin membuatku kaget dan tidak kuasa menahan air mata, “yuk aku anter kamu
pulang aja, untuk terakhir kalinya.”
Dengan bodohnya aku, aku tidak
mencoba melawan atau menjawab perkataan Bagas tadi. Aku setuju untuk diantar
pulang untuk terakhir kalinya tanpa usaha mempertahankan hubungan yang sudah
berjalan dua tahun itu. Diperjalanan pulang pun aku dan Bagas tidak berbincang
sama sekali, Bagas fokus menyetir, sedangkan aku fokus untuk menahan agar air
mata ini tidak kembali menetes.
Sesampainya di depan rumahku, aku melepaskan
cincin di jari manisku dan memberikannya kepada Bagas,
“Gas, nih aku balikin yaa..
terimakasih untuk dua tahun ini. Maafin kalau aku kurang berani untuk
memperjuangkan kamu di depan Ayah.”
Bagas hanya menunduk, menerima
cincin tersebut, dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun sampai aku turun dari
mobilnya.
Aku
sayang Bagas, aku cinta Bagas. Dengan semua kekurangan dan kelebihannya. Tanpa
melihat gelar dia, pendidikan dia, atau apapun itu. Aku percaya Bagas adalah
orang pintar, lelaki yang akan memperjuangkan apapun untukku. Sayangnya Ayah
dan Ibu terlalu menutup mata, terlalu dibutakan oleh materi. Lalu kenapa aku
sangat mudah untuk melepaskannya?
Hari
itu, tanggal 21 April 2012 menjadi hari terakhir aku berhubungan dan bertemu
dengan Bagas selama berbulan-bulan kemudian.
Keesokan harinya, Alisa langsung
mendatangiku ke kantor.
“lo kesambet apaan sih Nar? Lo cinta
kan sama Bagas?” nada suara Alisa saat itu sangat tidak enak di dengar.
“sayaaaang bangeeettttt dan
cintaaa banget Cha. Tapi gue harus gimana? Lo tau kali bokap gue kayak apa? Gue
pasti dituduh terlalu naif kalau terus mempertahankan Bagas, padahal kayaknya
udah nggak mungkin gue nikah sama dia.”
“iya lo naif, tapi bukan
gara-gara mempertahankan dia. Tapi karena dengan mudahnya melepaskan dia tanpa
coba usaha apapun. This is so not you.”
Katanya sembari menggeleng-gelengkan kepala.
Aku menelan ludah.
“yang namanya cinta tuh ya
menurut gue artinya akan dan saling memperjuangkan satu sama lain. Lo nggak
percaya kalau Bagas akan usaha buat ngasih makan lo dan anak-anak lo nanti? Dia
sayang kan Nar sama lo?”
Kalimat
terakhir Alisa saat itu akan selalu aku ingat sampai kapanpun. Ya aku yakin
kalau Bagas menyayangiku, mencintaiku, dan akan selalu berusaha untukku, untuk
kami.
*****
Bandung, Juli 2012
Kring
kring kring.
Aku kaget melihat layar handphone saat itu, nama Bagas muncul di
layar. Dengan ragu dan doa sebelumnya, akhirnya aku mengangkat telfon tersebut.
“halo,” kataku dengan nada ragu.
“Dinar? Bisa ketemu nggak?
Mumpung aku lagi di Bandung.” Bagas menjawab tanpa basa-basi sama sekali.
“hmm..boleh, mau ketemu dimana?”
jawabku setelah berpikir sejenak.
“cafe Halaman aja ya, aku ada
urusan dulu sih di Sabuga siangnya. Nggak apa-apa?”
“oke.”
Malamnya, selesai dari kantor aku
langsung menuju ke cafe Halaman, antara cemas dan senang
karena akhirnya bisa
bertemu lagi dengan Bagas setelah beberapa bulan hilang kontak. Sesampainya di
sana, aku sudah bisa melihat Bagas duduk di pojok ruangan sambil asik memainkan
handphone-nya
“Gas, maaf telat. Udah lama ya?”
tanyaku mencoba untuk basa-basi sambil memilih duduk di hadapannya.
“nggak juga kok, pesen dulu aja
Nar.” Bagas membalasnya dengan sangat ramah. Oh God, I really miss my this man.
Setelah berbasa-basi singkat,
menanyakan kabar masing-masing, kegiatan sehari-hari, akhirnya Bagas memulai
pembicaraan yang tampaknya lebih serius.
“hmm..Nar, kamu mungkin tau kalau
aku sampai saat ini masih sayang sama kamu. Niatku yang dulu belum pernah
berubah sampai saat ini. I want to marry
you, and you know that, right?”
Aku hanya mengangguk dan menahan
agar tidak lagi menangis.
“aku juga tau kalau orang tua
kamu, terutama Ayah akan sangat menolak aku di dalam keluargamu, kan? Karena
sampai saat ini aku belum punya pekerjaan yang tetap dan bahkan nggak lulus
kuliah.”
Aku kembali terdiam.
“tapi aku cuma mau nanya kamu
satu hal ini, satu kali aja. Do you love
me?” Bagas melanjutkan, kali ini bertanya.
Dengan sigap, dan kali ini tanpa
berbohong, aku langsung menjawab, “yes,
Gas. I do.”
Senyum Bagas mulai terlihat di
raut mukanya, “kamu mau kan ikut memperjuangkan hubungan kita? Karena aku nggak
bakalan sanggup kalau cuma usaha sendiri.”
Ucapan Bagas tadi dilanjutkannya
dengan berlutut (lagi) dihadapanku dengan memberikan cincin yang sama dengan 4
bulan lalu. Saat itu tak terasa air mataku menetes lagi, kali ini air mata
terharu dan bahagia. Aku menerima tawaran itu untuk kedua kalinya.
Iya
Bagas, aku siap dan mau memperjuangkan kamu sebesar kamu memperjuangkan aku
selama ini. Karena aku yakin pada Bagas, aku yakin ia
akan mampu menjadi suami dan bapak yang baik untuk anak-anaku kelak.
Perjalanan
kami setelah itu memang tidak mudah, ayah dan ibuku sulit untuk diyakinkan.
Mereka masih selalu beranggapan bahwa Bagas tidak akan mampu membiayai
keluarganya kelak. Bagas diharuskan menyanggupi beberapa syarat sampai akhirnya
diterima oleh ayah. Salah satunya adalah mempunyai rumah sendiri dan memulai
bisnis.
*****
Jakarta, Juni 2016
“sayang, maaf yaa telat. Tadi shooting-nya ngaret” Bagas datang sambil mencium keningku sebelum akhirnya duduk
disampingku.
Aku tersenyum, “iyaa, sayang,
nggak apa-apa. Happy anniversary yaa.”
Balasku sambil memberikan sebuah kotak sebagai hadiah ulang tahun pernikahan
kami yang ketiga.
“apaan ini?” ucap Bagas sembari
membuka kotak tersebut. Aku dapat melihat senyumnya ketika dia melihat apa yang
ada di dalam kotak tersebut. “aku akan jadi ayah?!” tanya Bagas sedikit
berteriak karena saking excited-nya.
Aku mengangguk sambil tersenyum.
Bagas langsung memeluku dengan sangat kencang, sampai aku hampir tidak bisa
bernafas.
“Gas, udah dong aku nggak bisa
nafas nih.” Kataku memelas.
Bagas tertawa kecil.
“terima kasih ya, sayang.” Ucap
Bagas sambil melepaskan pelukannya.
Mungkin
memang benar kalau materi atau uang menjadi objek yang paling mendasar untuk
kita hidup. Dengan adanya uang hidup akan jauh terasa lebih mudah, namun bukan
berarti kita boleh melupakan sumber kehidupan lain yang sama pentingnya, yaitu
cinta. Memang, kita tidak akan kenyang dengan cinta, tidak bisa membeli
keperluan sehari-hari dengan cinta. Namun, bersama orang yang kita cintai dan
mencintai kita akan membuat kita merasa lebih nyaman dan aman. Dengan mereka
kita akan lebih mudah berpikir, mengekspresikan diri, menjadi orang yang lebih
baik, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk pasangan kita. Hal itulah
yang aku dapatkan dari Bagas, dengan cintanya yang besar dia dapat
memperjuangkan dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia bisa membiayai aku
dan keluarga kecil kami jauh diatas yang orang harapkan, lebih dari cukup. Ya,
cinta memang butuh perjuangan, namun dengan cinta, perjuangan yang sulit pun
akan terasa mudah.
“Love
is not about accepting. But it’s about understanding and fighting for someone
you loved”
Blog post ini dibuat dalam rangka mengikuti Kompetisi Menulis Cerpen "Pilih Mana: Cinta Atau Uang?" #KeputusanCerdas yang diselenggarakan oleh www.cekaja.com dan Nulisbuku.com.